The only hypnotherapy school in Indonesia approved by American Council of Hypnotist Examiners (ACHE), USA
Artikel

Psikologi Dalam
15 Juli 2024Psikologi dalam (deep psychology), menurut American Psychological Association (APA, 2007), adalah sebuah pendekatan umum terhadap psikologi dan psikoterapi yang berfokus pada proses mental bawah sadar sebagai sumber gangguan dan gejala emosional, serta kepribadian, sikap, kreativitas, dan gaya hidup.
Psikologi dalam mengacu pada eksplorasi mendalam terhadap pikiran, emosi, perilaku, dan pengalaman manusia, menyelidiki mekanisme yang mendasari yang membentuk pikiran dan tindakan individu. Meskipun istilah "psikologi dalam" tidak umum digunakan sebagai konsep yang berdiri sendiri dalam literatur akademis, istilah ini dapat dipahami sebagai pendekatan komprehensif untuk memahami kompleksitas psikologi manusia pada tingkat yang mendalam.
Konsep psikologi dalam dapat dikaitkan dengan berbagai aspek penyelidikan psikologis, seperti mengeksplorasi proses bawah sadar, menganalisis kondisi emosional yang kompleks, menyelidiki motivasi yang mendasari, dan memahami seluk-beluk perilaku manusia. Psikologi dalam dapat melibatkan penggalian ke kedalaman pikiran bawah sadar untuk mengungkap keyakinan, trauma, dan pola tersembunyi yang memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang.
Dalam konteks referensi yang diberikan, psikologi dalam dapat dikaitkan dengan eksplorasi pengalaman emosional yang mendalam, dampak faktor psikologis terhadap perilaku, dan interaksi yang rumit antara kognisi, emosi, dan motivasi. Sebagai contoh, penelitian tentang empati, tekanan psikologis, kerja afektif, dan pengalaman emosional dalam berbagai konteks menjelaskan proses psikologis yang mengakar yang membentuk interaksi manusia, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan.
Selain itu, konsep psikologi dalam juga dapat mencakup pemeriksaan dimensi eksistensial, spiritual, atau transpersonal dari pengalaman manusia. Hal ini dapat melibatkan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang makna, tujuan, identitas, dan pertumbuhan pribadi dari perspektif psikologis yang melampaui kerangka kerja kognitif dan perilaku tradisional.
Walau sulit untuk menemukan definisi standar "psikologi dalam" dalam literatur akademis, istilah ini dapat dikonseptualisasikan sebagai pendekatan holistik dan mendalam untuk memahami kompleksitas psikologi, emosi, dan perilaku manusia. Dengan menyelidiki kedalaman pikiran bawah sadar manusia, psikologi dalam berusaha mengungkap faktor-faktor mendasar yang mendorong pengalaman individu dan membentuk kesejahteraan psikologis.
Psikologi dalam merupakan eksplorasi yang rumit dan komprehensif terhadap cara kerja pikiran, emosi, dan perilaku manusia yang rumit, yang bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek tersembunyi dari batin dan memberikan wawasan ke dalam kompleksitas mendalam psikologi manusia.

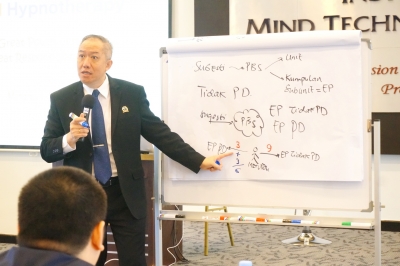
Hipnoanalisis
11 Juli 2024

Uji Hasil Terapi: Kewajiban Terapis dan Hak Klien
5 Juli 2024Hipnoterapi adalah proses terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis, bisa menggunakan teknik apa saja. Terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan dalam hipnoterapi: bebas konten dan berbasis konten.
Yang dimaksud dengan bebas konten (content free) adalah terapi dilakukan tanpa harus menemukan dan memproses akar masalah. Termasuk dalam pendekatan ini adalah hipnoterapi yang mengandalkan sugesti dan teknik-teknik NLP seperti mengubah strategi perilaku, submodality change, collapsing anchor, power trigger, reverse trigger, fast phobia cure, six step reframing, dan visual squash. Uraian tentang teknik-teknik NLP ini saya jelaskan detil di buku The Secret of Mindset.
Sementara hipnoterapi berbasis konten, biasa disebut sebagai hipnoanalisis, mengutamakan pencarian akar masalah, kejadian paling awal atau rangkaian kejadian, yang menjadi sumber masalah emosi atau perilaku yang klien alami, dan melakukan resolusi pada kejadian-kejadian ini.
Apa pun pendekatan yang digunakan adalah baik karena bertujuan membantu klien mengatasi masalah. Namun ada satu hal sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap hipnoterapis, terlepas dari pendekatan terapi yang ia gunakan. Usai melakukan terapi pada klien, terapis wajib melakukan uji hasil terapi, untuk memastikan terapi yang ia lakukan benar-benar berhasil mencapai tujuan terapeutik yang diharapkan.
Uji hasil terapi harus menjadi satu dengan protokol terapi yang digunakan oleh terapis. Mengingat yang diproses adalah pikiran bawah sadar, hasil terapi tidak perlu menunggu klien pulang ke rumah, besok, lusa, satu atau dua minggu pascaterapi. Hasil terapi bisa langsung diuji dan diketahui usai terapi dilakukan.
Misalnya klien datang dengan masalah fobia jarum suntik. Terapis profesional akan melakukan pre-test dengan meminta klien seolah sedang bertemu dengan jarum suntik. Ini bisa dilakukan secara imajinatif, dengan meminta klien menutup mata dan membayangkan jarum suntik, atau dengan menunjukkan gambar jarum suntik. Tentu akan sangat baik bila terapis menunjukkan jarum suntik riil pada klien.
Saat klien membayangkan atau melihat gambar jarum suntik, ia pasti menunjukkan reaksi emosi negatif seperti takut, cemas, ngeri, dan tubuhnya juga bereaksi, jantung berdebar, napas memburu. Respons tubuh ini adalah indikasi kondisi lawan (fight) atau lari (flight).
Ini adalah pre-test yang wajib dilakukan oleh terapis profesional karena berfungsi sebagai referensi guna dibandingkan dengan hasil terapi.
Usai terapi, hipnoterapis wajib melakukan uji hasil terapi atau post-test. Caranya adalah dengan menunjukkan gambar yang sama pada klien. Terapis melihat dan membandingkan reaksi klien, sebelum dan sesudah terapi.
Terapi yang efektif pasti berdampak positif. Harusnya, setelah terapi, bila klien melihat gambar yang sama, ia tidak bereaksi negatif seperti sebelumnya.
Bila ternyata klien tetap merasa takut atau ngeri, saat melihat jarum suntik, dengan intensitas yang tidak menurun atau hanya berkurang sedikit, ini menunjukkan terapinya tidak efektif.
Bila terapis melakukan terapi pada klien, menggunakan pendekatan yang sama, untuk mengatasi masalah yang sama, selama beberapa sesi, dan klien tetap tidak mengalami perubahan, terapis harus tahu diri. Jangan lanjutkan terapi. Sarankan klien untuk mencari hipnoterapis lain yang lebih kompeten untuk membantu mengatasi masalahnya.
Untuk mampu melakukan terapi dengan efektif sangat dibutuh rasa percaya diri. Namun, yang lebih penting adalah tahu diri. Dan yang paling penting adalah sadar diri. Bila memang kompetensi terapis tidak mampu untuk membantu klien mengatasi masalahnya, terapis harus berani dan jujur menyampaikan hal ini pada klien. Inilah profesionalisme yang harus ditunjukkan terapis.
Hipnoterapis AWGI menggunakan standar komitmen maksimal 4 sesi untuk mengatasi satu masalah. Klien tidak harus menjalani sampai 4 sesi terapi. Bila dalam satu atau dua sesi masalah klien sudah berhasil diatasi, terapi dihentikan. Bila, misal, sampai 4 sesi masalah klien tidak tuntas terselesaikan, hipnoterapis AWGI harus menghentikan sesi terapi dan merujuk klien ke hipnoterapis AWGI lain yang lebih senior.
Hipnoterapis AWGI dilarang dengan sengaja memperpanjang sesi terapi bila ternyata ia tidak mampu membantu klien mengatasi masalahnya dengan tuntas dalam maksimal 4 sesi terapi. Ini bertujuan untuk melindungi klien agar tidak mengeluarkan biaya terapi yang tidak perlu akibat terapis yang tidak kompeten dan tidak sadar diri. Ini juga yang mendasari aturan hipnoterapis AWGI dilarang mengenakan biaya terapi dengan sistem paket atau borongan.
Contoh kasus di atas adalah kasus ringan, fobia jarum suntik. Bagaimana dengan kasus berat? Sama saja, hipnoterapis wajib melakukan uji hasil terapi.
Dengan demikian, validasi hasil terapi dilakukan melalui dua tahap, yaitu pertama, dengan uji hasil terapi yang dilakukan usai terapi, di ruang praktik, dan kedua melalui laporan yang disampaikan klien pada terapis setelah klien pulang ke rumah, menjalani hidupnya seperti biasa dan bertemu dengan hal, situasi, kondisi, orang, atau objek yang sebelumnya membuat klien tidak nyaman.
Apabila dua validasi ini memberikan hasil positif, klien dinyatakan sembuh dan tidak perlu melanjutkan terapi ke sesi berikutnya.
Uji hasil terapi adalah salah satu bentuk profesionalisme, uji kompetensi, dan tanggungjawab hipnoterapis pada klien, dan adalah hak klien yang harus dipenuhi oleh terapis.
Sebagai klien, anda harus tahu hak anda. Bila terapis anda tidak melakukan uji hasil terapi, usai ia menerapi anda, anda berhak minta terapis anda melakukannya. Bila terapis anda tidak bersedia melakukan uji hasil terapi, anda bisa melakukannya sendiri.
Caranya sangat mudah. Anda cukup tutup mata dan mengingat kembali kejadian, situasi, kondisi, orang, atau objek yang sebelumnya membuat anda merasa tidak nyaman. Bila terapinya efektif atau berhasil, saat anda mengingat kembali kejadiannya, perasaan anda netral. Ini artinya masalah anda telah berhasil diatasi.
Bila ternyata saat anda mengingat kembali objek itu dan anda masih merasa tidak nyaman, emosi anda masih bergejolak, tidak ada penurunan intensitas atau intensitas hanya turun sedikit, anda perlu segera menyampaikan ini pada terapis anda agar ia tahu yang anda alami dan rasakan.
Ingat, uji hasil terapi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap terapis dan sekaligus adalah hak anda sebagai klien, yang harus anda dapatkan. Setiap terapis profesional pasti melakukan uji hasil terapi sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada klien.


Teori Hipnosis
27 Juni 2024Pendahuluan
Hipnosis, yang merupakan keadaan perhatian terfokus, peningkatan sugestibilitas, dan relaksasi mendalam, telah memikat perhatian para ilmuwan, psikolog, dan masyarakat umum selama berabad-abad. Meskipun penelitian yang luas telah dilakukan, hipnosis tetap menjadi fenomena yang kompleks dan sering disalahpahami.
Menghadapi subjek yang sekompleks hipnosis, ketidakmampuan satu teori tunggal untuk menjelaskan berbagai respons dalam banyak dimensi pengalaman menjadi sangat jelas. Kompleksitas hipnosis, serta kompleksitas yang lebih besar dari manusia yang mampu mengalami hipnosis, sangat besar sehingga tampaknya sangat tidak mungkin satu teori tunggal dapat berkembang untuk menjelaskan asal usul dan karakteristik hipnosis.
Walau terdapat banyak teori tentang hiposis diajukan para pakar dan ilmuwan, sebagian besar teori yang diajukan dapat secara longgar diklasifikasikan sebagai teori kondisi dan non-kondisi, intrapersonal dan interpersonal, teori tunggal dan multifaktor (Yapko, 2003).
Teoretikus kondisi, intrapersonal, dan tunggal mengkonseptualisasikan hipnosis sebagai keadaan trans atau keadaan kesadaran yang berubah (Barber, 1969). Para teoretikus non-kondisi, interpersonal, dan multifaktor, yang juga dikenal sebagai teoretikus sosiokognitif, mengedepankan penjelasan sosial-psikologis tentang hipnosis. Para teoretikus ini berpendapat bahwa tidak ada yang unik tentang hipnosis dan berargumen bahwa sebagian besar fenomena hipnosis dapat terjadi tanpa induksi hipnotik atau trans (Barber, 1979).
Teori intrapersonal hipnosis menekankan keadaan subjektif dan batin dari orang yang dihipnosis, sementara model interpersonal lebih menekankan konteks sosial atau aspek relasional dari interaksi hipnosis (Yapko, 2003).
Model tunggal hipnosis menekankan pentingnya satu variabel seperti relaksasi atau disosiasi yang mempengaruhi pengalaman hipnosis. Pendekatan multifaktor menekankan peran berbagai kekuatan interaksional, seperti harapan pasien dan tuntutan klinisi, yang berperan dalam menghasilkan fenomena hipnosis (Kirsch, 2000).
Meskipun tidak ada satu pun teori di antara teori-teori ini yang mampu secara memuaskan menjelaskan semua fenomena yang terkait dengan hipnosis, berbagai formulasi tersebut telah memperluas pemahaman kita tentang subjek ini. Membahas kelebihan dan kontroversi seputar setiap teori melampaui cakupan tulisan ini (lihat Kallio dan Revonsuo, 2003, untuk tinjauan, dan tanggapan dalam seluruh edisi Contemporary Hypnosis, 2005; 22(1): 1–55).
Seturut simpulan Rowley (1986, p. 23), dari tinjauannya tentang teori-teori hipnosis terkenal:
"Tidak satu pun dari mereka tampaknya mampu menjelaskan semua fenomena yang berada di bawah judul besar hipnosis secara memadai. Hal ini tidak mengherankan mengingat variasi fenomena yang sangat besar. Oleh karena itu, teori-teori tersebut memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan variasi ini. Beberapa mendefinisikan ulang hipnosis, misalnya Edmonston (1981). Yang lain menafsirkan ulang pengalaman subjektif, misalnya Spanos (1982). Meskipun terdapat kekurangan, masing-masing teori memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan, seperti konseptualisasi baru dari masalah, pendekatan metodologis, atau sintesis baru dari bukti yang ada. Tentu saja, tidak mungkin menghasilkan teori yang memuaskan semua peneliti, karena mereka memiliki kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi teori-teori tersebut."
Berdasar uraian di atas, tulisan ini bertujuan mengeksplorasi berbagai teori hipnosis, mengkaji perspektif sejarah, model psikologis, dan pemahaman ilmiah kontemporer, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa hipnosis bekerja.
Perspektif Sejarah
Mesmerisme dan Magnetisme Hewan
Sejarah hipnosis dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-18 kepada Franz Anton Mesmer, seorang dokter Austria yang memperkenalkan konsep magnetisme hewan. Mesmer percaya bahwa transfer energi alami, yang ia sebut sebagai "magnetisme hewan", dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang. Metodenya melibatkan penggunaan magnet dan tangannya sendiri untuk mengarahkan energi ini kepada pasiennya, menyebabkan keadaan seperti trans yang diyakini dapat mempercepat penyembuhan (Gauld, 1992).
Teori-teori Mesmer, meskipun kemudian dibantah, meletakkan dasar bagi perkembangan hipnosis. Mesmerisme menjadi populer di Eropa dan mempengaruhi banyak pemikir dan praktisi berikutnya. Para pengikut Mesmer, yang dikenal sebagai mesmeris, terus menggunakan teknik-tekniknya, yang akhirnya berevolusi menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai hipnosis.
James Braid dan Hipnosis
Istilah "hipnosis" diciptakan oleh James Braid, seorang ahli bedah asal Skotlandia, pada pertengahan abad ke-19. Braid menolak konsep Mesmer tentang magnetisme hewan dan sebaliknya menyatakan bahwa hipnosis adalah fenomena psikologis. Dia mengamati bahwa individu dapat memasuki kondisi seperti trans melalui perhatian yang terfokus dan relaksasi, tanpa memerlukan kekuatan magnet. Karya Braid sangat penting dalam menggeser pemahaman tentang hipnosis dari perspektif mistik ke perspektif ilmiah (Braid, 1843).
Karya perintis Braid mencakup penggunaan teknik tatapan tetap, di mana subjek diminta untuk fokus pada satu titik tertentu untuk menginduksi kondisi hipnosis. Dia percaya bahwa hipnosis adalah bentuk "tidur saraf" dan bahwa itu dapat digunakan sebagai terapi untuk mengobati berbagai penyakit.
Sekolah Nancy dan Sekolah Paris
Pada akhir abad ke-19, dua aliran pemikiran utama muncul dalam studi hipnosis: Sekolah Nancy dan Sekolah Paris.
Sekolah Nancy, dipimpin oleh Ambroise-Auguste Liébeault dan Hippolyte Bernheim, menekankan peran sugesti dalam hipnosis. Mereka percaya bahwa hipnosis adalah fenomena psikologis normal yang dapat diinduksi pada siapa saja melalui sugesti.
Sementara Sekolah Paris, dipimpin oleh Jean-Martin Charcot, memandang hipnosis sebagai keadaan patologis yang terkait dengan histeria. Karya Charcot berfokus pada penggunaan hipnosis dalam studi dan pengobatan gangguan neurologis. Perdebatan antara kedua sekolah ini membantu memperjelas dan mengembangkan dasar teoritis hipnosis.
Teori Psikologi
Teori Disosiasi
Salah satu teori psikologi paling berpengaruh tentang hipnosis adalah teori disosiasi, yang terutama dikaitkan dengan karya Pierre Janet dan kemudian, Ernest Hilgard. Disosiasi merujuk pada pemisahan dalam kesadaran, di mana pikiran, perasaan, atau perilaku tertentu menjadi terpisah dari kesadaran individu secara keseluruhan (Hilgard, 1977).
Teori neodisosiasi Hilgard mengembangkan konsep ini, dengan menyatakan bahwa hipnosis melibatkan pembagian kesadaran menjadi beberapa aliran. Satu aliran kesadaran tetap sadar akan lingkungan eksternal, sementara aliran kesadaran lainnya fokus pada sugesti dari operator (orang yang melakukan hipnosis). Pembagian ini memungkinkan terjadinya pengalaman hipnosis, di mana individu dapat melakukan tindakan atau mengingat kembali ingatan tanpa kesadaran sadar.
Penelitian Hilgard mencakup eksperimen dengan fenomena "pengamat tersembunyi", di mana subjek yang berada dalam kondisi hipnosis melaporkan bagian diri mereka yang terpisah dan tersembunyi, yang sadar akan apa yang terjadi selama hipnosis. Hal ini memberikan bukti untuk sifat disosiatif dari hipnosis dan mendukung gagasan bahwa ada beberapa tingkat kesadaran yang terlibat.
Teori Sosial-Kognitif
Teori sosial-kognitif tentang hipnosis, yang dikembangkan oleh Theodore Sarbin dan Nicholas Spanos, menyatakan bahwa hipnosis bukanlah suatu kondisi kesadaran yang unik, melainkan suatu bentuk permainan peran. Menurut teori ini, individu yang mengalami hipnosis termotivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan operator dan konteks sosial. Mereka pada dasarnya "memainkan peran" sebagai orang yang terhipnosis, mengikuti sugesti yang diberikan (Spanos, 1986).
Teori ini menekankan pentingnya faktor sosial dan kognitif dalam membentuk pengalaman hipnosis. Teori ini menyatakan bahwa trans hipnosis adalah produk dari proses psikologis normal, seperti imajinasi, kepercayaan, dan pengaruh sosial. Sarbin dan Spanos berpendapat bahwa perilaku individu dalam kondisi hipnosis dapat dijelaskan dengan kesediaan mereka mematuhi instruksi operator dan pengharapan sosial yang terkait dengan hipnosis.
Teori Kondisi
Teori kondisi hipnosis berpendapat bahwa hipnosis adalah keadaan kesadaran yang berbeda, berbeda dari keadaan terjaga dan tidur. Para pendukung pandangan ini, seperti John Kihlstrom, berpendapat bahwa hipnosis melibatkan perubahan fisiologis dan neurologis tertentu yang membedakannya dari kondisi pikiran biasa (Kihlstrom, 2007).
Penelitian di bidang ini berfokus pada identifikasi perubahan-perubahan ini, seperti perubahan pola aktivitas otak, tingkat neurokimia, dan respons sistem saraf otonom. Teoretikus teori kondisi menyatakan bahwa penanda fisiologis ini memberikan bukti bahwa hipnosis adalah kondisi kesadaran yang unik.
Teori Non-Kondisi
Berbeda dengan teori kondisi, teori non-kondisi menyatakan bahwa hipnosis tidak melibatkan kondisi kesadaran khusus. Sebaliknya, hipnosis dipandang sebagai interaksi kompleks dari proses psikologis, seperti perhatian yang terfokus, pengharapan, dan pengaruh sosial. Perspektif non-kondisi sejalan dengan teori sosial-kognitif dan menekankan bahwa hipnosis dapat dijelaskan dengan mekanisme kognitif dan sosial biasa (Kirsch & Lynn, 1995).
Para pendukung teori non-kondisi berpendapat bahwa efek hipnosis terutama disebabkan oleh kekuatan sugesti dan daya tanggap individu terhadap sugesti tersebut. Pandangan ini menantang gagasan bahwa hipnosis adalah keadaan fisiologis atau neurologis yang berbeda. Teori respons pengharapan Irving Kirsch, misalnya, menyatakan bahwa pengharapan individu tentang efek hipnosis memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman hipnosis mereka.
Teori Neurobiologis
Peran Otak dalam Hipnosis
Kemajuan dalam neurosains telah memberikan wawasan baru tentang dasar-dasar neurobiologis hipnosis. Para peneliti telah menggunakan teknik-teknik seperti pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI) dan elektroensefalografi (EEG) untuk mempelajari aktivitas otak selama hipnosis.
Salah satu temuan utama adalah bahwa hipnosis melibatkan perubahan di daerah otak yang terkait dengan perhatian, seperti korteks cingulate anterior, korteks prefrontal, dan talamus. Area-area ini terlibat dalam mengatur perhatian, mengendalikan fungsi eksekutif, dan memodulasi persepsi sensorik. Penelitian telah menunjukkan bahwa selama hipnosis, terjadi peningkatan konektivitas di antara daerah-daerah ini, menunjukkan keadaan perhatian yang terfokus (Oakley & Halligan, 2013)
Jaringan Mode Default dan Hipnosis
Jaringan Mode Default (Default Mode Network / DMN) adalah jaringan daerah otak yang aktif ketika pikiran sedang beristirahat dan tidak terfokus pada lingkungan eksternal. DMN terkait dengan pemikiran yang berhubungan dengan diri sendiri, pikiran mengembara, dan pemrosesan memori autobiografi.
Penelitian telah mengindikasikan bahwa hipnosis dapat menyebabkan penurunan aktivitas DMN, yang dapat menjelaskan pengalaman disosiasi dan perubahan kesadaran diri selama hipnosis. Dengan menenangkan DMN, hipnosis memungkinkan pengalaman yang lebih fokus dan mendalam, memfasilitasi penerimaan sugesti (Landry, Lifshitz, & Raz, 2017).
Perubahan Neurokimia
Perubahan neurokimia juga berperan dalam hipnosis. Penelitian telah menunjukkan bahwa hipnosis dapat mengubah tingkat neurotransmiter tertentu, seperti dopamin dan serotonin. Perubahan ini dapat memengaruhi suasana hati, persepsi, dan kemampuan memproses sugesti.
Peningkatan kadar dopamin telah dikaitkan dengan peningkatan sugestibilitas, sementara perubahan kadar serotonin dapat memengaruhi suasana hati dan kecemasan. Memahami perubahan neurokimia ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mekanisme yang mendasari hipnosis (Vanhaudenhuyse et al., 2014).
Hipnosis dan Gelombang Otak
Penelitian juga telah mengeksplorasi hubungan antara hipnosis dan aktivitas gelombang otak. Studi elektroensefalografi (EEG) telah menunjukkan bahwa hipnosis dapat menyebabkan perubahan pola gelombang otak, terutama pada rentang frekuensi alfa dan theta. Pola gelombang otak ini dikaitkan dengan keadaan relaksasi, perhatian yang terfokus, dan meditasi yang mendalam.
Gelombang alfa (8-12 Hz) biasanya terlihat saat keadaan rileks dan terjaga, sedangkan gelombang theta (4-8 Hz) berhubungan dengan tidur ringan dan meditasi yang dalam. Selama hipnosis, sering kali terjadi peningkatan aktivitas alfa dan theta, yang mencerminkan keadaan rileks dan fokus dari individu yang sedang berada dalam kondisi hipnosis (Williams & Gruzelier, 2001).
Aplikasi dan Teori Klinis
Hipnosis untuk Manajemen Nyeri
Salah satu aplikasi klinis hipnosis yang paling terdokumentasi dengan baik adalah dalam manajemen nyeri. Hipnosis telah terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit akut dan kronis. Teori yang menjelaskan efek ini termasuk teori pengendalian gerbang rasa sakit (gate control theory of pain), yang menunjukkan bahwa hipnosis dapat memodulasi jalur saraf yang terlibat dalam persepsi rasa sakit (Montgomery et al., 2000).
Dengan mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan mengubah persepsi individu terhadapnya, hipnosis dapat secara efektif mengurangi rasa sakit. Hal ini didukung oleh studi pencitraan saraf yang menunjukkan perubahan aktivitas otak di area yang terkait dengan pemrosesan nyeri selama hipnosis (Derbyshire et al., 2004).
Hipnosis telah digunakan dalam berbagai konteks medis, seperti selama operasi untuk mengurangi kebutuhan akan anestesi, pada kondisi nyeri kronis seperti fibromialgia, dan dalam mengelola nyeri yang terkait dengan pengobatan kanker. Penggunaan hipnosis dalam konteks ini menguatkan potensinya sebagai intervensi non-farmakologis untuk meredakan nyeri.
Hipnosis dalam Psikoterapi
Hipnosis juga digunakan dalam psikoterapi, terutama dalam pengobatan kondisi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Hipnoterapi melibatkan penggunaan hipnosis untuk memfasilitasi proses terapi, seperti mengungkap ingatan yang tertekan, mengubah pola pikir yang disfungsional, dan meningkatkan relaksasi.
Teori yang menjelaskan keefektifan hipnoterapi mencakup gagasan bahwa hipnosis meningkatkan kemampuan individu untuk mengakses dan memproses materi bawah sadar. Hal ini dapat menghasilkan wawasan dan perubahan perilaku yang sulit dicapai melalui metode terapi tradisional (Heap & Aravind, 2002).
Teknik hipnoterapi seperti regresi usia (age regression), citra terpandu (guided imagery), dan penguatan ego (ego-strengthening), digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis yang mendasarinya. Aliansi terapeutik antara hipnoterapis dan klien, bersama dengan kesediaan klien untuk terlibat dalam proses terapi, memainkan peran penting dalam keberhasilan hipnoterapi.
Hipnosis untuk Pengendalian Kebiasaan
Hipnosis telah digunakan untuk membantu individu mengubah kebiasaan, seperti berhenti merokok dan menurunkan berat badan. Teori-teori yang menjelaskan aplikasi ini menunjukkan bahwa hipnosis dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat perilaku positif melalui kekuatan sugesti. Dengan menciptakan kondisi yang fokus dan reseptif, hipnosis dapat memudahkan individu untuk mengadopsi kebiasaan baru dan menolak kebiasaan lama (Green & Lynn, 2000).
Penelitian telah menunjukkan bahwa hipnoterapi efektif dalam membantu individu berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan mengatur perilaku makan. Hipnosis bekerja dengan menargetkan pikiran bawah sadar, di mana kebiasaan dan perilaku yang bersifat otomatis disimpan, dan dengan memperkuat komitmen individu untuk berubah.
Hipnosis dalam Prosedur Medis
Hipnosis juga telah digunakan untuk memfasilitasi berbagai prosedur medis. Prosedur tindakan gigi, persalinan (hypnobirthing), dan endoskopi gastrointestinal telah mendapatkan manfaat dari penggunaan hipnosis untuk mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan. Hipnosis dapat membantu pasien tetap tenang dan kooperatif selama menjalani prosedur medis, meningkatkan pengalaman positif secara keseluruhan dan berpotensi mengurangi kebutuhan akan intervensi farmakologis.
Teori-teori yang menjelaskan keefektifan hipnosis dalam prosedur medis mengutamakan peran relaksasi, perhatian yang terfokus, dan pengurangan kecemasan. Dengan memanfaatkan keadaan relaksasi yang mendalam dan perhatian yang terfokus, hipnosis dapat membantu pasien mengelola rasa takut dan ketidaknyamanan mereka, yang mengarah pada pengalaman yang lebih lancar dan lebih positif (Lang et al., 2000).
Teori dan Penelitian Kontemporer
Model-model Hipnosis yang Terintegrasi
Teori kontemporer tentang hipnosis sering kali mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, model biopsikososial mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam menjelaskan pengalaman hipnosis. Model ini mengakui bahwa hipnosis melibatkan interaksi yang kompleks antara aktivitas otak, proses kognitif, dan pengaruh sosial (Jensen et al., 2015).
Model terpadu mengakui bahwa tidak ada satu teori pun yang dapat sepenuhnya menjelaskan beragam fenomena yang terkait dengan hipnosis. Sebaliknya, mereka mengusulkan bahwa hipnosis merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, termasuk perbedaan individu dalam hal sugestibilitas, peran sugesti dan pengharapan, serta teknik spesifik yang digunakan oleh operator.
Peran Perbedaan Individu
Penelitian telah menunjukkan bahwa perbedaan individu, seperti ciri-ciri kepribadian dan sugestibilitas memainkan peran penting dalam pengalaman hipnosis. Individu dengan sugestibilitas tinggi cenderung memiliki karakteristik khusus, seperti tingkat penyerapan dan imajinasi yang tinggi.
Teori-teori yang berfokus pada perbedaan individu menunjukkan bahwa sifat-sifat ini membuat beberapa orang lebih responsif terhadap hipnosis dan lebih mungkin mengalami kondisi hipnosis yang dalam. Memahami perbedaan individu ini penting untuk menyesuaikan intervensi hipnosis untuk memaksimalkan keefektifannya (Cardeña & Terhune, 2014).
Hipnotisabilitas sering dinilai menggunakan skala standar, seperti Stanford Hypnotic Susceptibility Scales (SHSS) dan Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS). Penilaian ini membantu peneliti dan klinisi mengidentifikasi individu yang lebih mudah mengalami dan mendapatkan manfaat dari hipnosis.
Hipnosis dan Plasebo
Ada ketertarikan yang semakin besar terhadap hubungan antara hipnosis dan efek plasebo. Keduanya melibatkan kekuatan sugesti dan harapan individu akan manfaat. Teori-teori di bidang ini menunjukkan bahwa hipnosis dan plasebo mungkin memiliki mekanisme yang sama, seperti aktivasi daerah otak yang terlibat dalam pengharapan dan penghargaan (Raz, 2007).
Mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara hipnosis dan plasebo dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sugesti memengaruhi pikiran dan tubuh, dan bagaimana mekanisme ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan terapeutik. Efek plasebo menekankan pentingnya keyakinan dan harapan klien dalam proses penyembuhan, yang juga merupakan komponen utama hipnosis.
Hipnosis dan Kesadaran
Hipnosis memberikan jendela unik ke dalam studi kesadaran. Teori-teori kesadaran, seperti Teori Ruang Kerja Global (Global Workspace Theory / GWT) dan Teori Informasi Terpadu (Integrated Information Theory), dapat diterapkan untuk memahami perubahan pengalaman sadar yang terjadi selama hipnosis.
Teori Ruang Kerja Global, yang diusulkan oleh Bernard Baars, menyatakan bahwa kesadaran muncul dari integrasi informasi di berbagai wilayah otak. Hipnosis dapat mengubah fungsi ruang kerja global ini, yang mengarah pada perubahan kesadaran dan pemrosesan informasi.
Teori Informasi Terpadu, yang dikembangkan oleh Giulio Tononi, menyatakan bahwa kesadaran adalah ukuran kemampuan otak untuk mengintegrasikan informasi. Hipnosis dapat memengaruhi kapasitas otak untuk integrasi, yang mengarah pada perubahan kondisi kesadaran dan perubahan pengalaman subjektif.
Peran Pengharapan dan Keyakinan
Pengharapan dan keyakinan memainkan peran penting dalam pengalaman hipnosis. Teori-teori di bidang ini menyatakan bahwa pengharapan seseorang tentang efek hipnosis dapat secara signifikan memengaruhi respons mereka terhadap sugesti hipnosis. Teori respons pengharapan, yang diusulkan oleh Irving Kirsch, menyatakan bahwa pengharapan yang dimiliki individu tentang hasil hipnosis dapat membentuk pengalaman dan perilaku aktual mereka (Kirsch, 1997).
Keyakinan akan keampuhan hipnosis, kepercayaan terhadap operator, dan pengharapan positif mengenai proses hipnosis dapat meningkatkan pengalaman hipnosis. Sebaliknya, keraguan dan pengharapan negatif dapat menghambat efektivitas hipnosis. Hal ini menekankan pentingnya membangun hubungan terapeutik yang positif dan membina lingkungan yang mendukung hipnosis.
Peran Imajinasi
Imajinasi adalah komponen kunci dari pengalaman hipnosis. Teori-teori menunjukkan bahwa hipnosis melibatkan keterlibatan imajinatif yang tinggi, di mana individu dapat dengan jelas membayangkan skenario, sensasi, dan pengalaman seolah-olah itu nyata. Keterlibatan imajinatif ini dapat memfasilitasi penerimaan sugesti hipnosis dan penciptaan persepsi yang berubah.
Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang sangat mudah mengalami kondisi hipnosis sering kali memiliki kemampuan imajinatif yang kuat dan kecenderungan ketercerapan yang tinggi, yang merupakan kapasitas untuk sepenuhnya larut dalam pengalaman imajinatif. Memahami peran imajinasi dalam hipnosis dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sugesti hipnosis diinternalisasi dan dijalankan (Tellegen & Atkinson, 1974).
Hipnosis dan Memori
Hipnosis telah digunakan untuk mengeksplorasi dan mempengaruhi proses memori. Teori-teori di bidang ini menunjukkan bahwa hipnosis dapat meningkatkan pemanggilan kembali memori, mengubah pengalaman subjektif dari peristiwa masa lalu, dan menciptakan memori palsu. Penggunaan hipnosis dalam konteks forensik dan terapeutik telah menimbulkan kekhawatiran etis dan metodologis, terutama mengenai keandalan memori yang diungkap menggunakan hipnosis.
Penelitian tentang hipnosis dan memori telah menunjukkan bahwa meskipun hipnosis dapat meningkatkan kepercayaan pada memori yang diingat kembali, namun tidak serta merta meningkatkan keakuratannya. Sugesti hipnosis dapat mengarah pada penciptaan memori yang jelas tetapi tidak akurat, menekankan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan hipnosis untuk pemanggilan kembali memori (Lynn et al., 2015).
Pertimbangan Etis dan Kontroversi
Penggunaan Hipnosis secara Etis
Penggunaan hipnosis dalam konteks klinis dan penelitian menimbulkan pertimbangan etika yang penting. Hipnoterapis dan peneliti harus memastikan bahwa hipnosis digunakan dengan cara yang aman, penuh hormat, bertanggungjawab, dan etis. Hal ini termasuk mendapatkan persetujuan, menjaga kerahasiaan, dan menghindari paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya.
Pedoman etika penggunaan hipnosis menekankan pentingnya menghormati otonomi dan martabat individu yang menjalani hipnosis. Praktisi harus memberikan informasi yang jelas tentang karakteristik hipnosis, potensi manfaat dan risikonya, dan pilihan pengobatan alternatif.
Kontroversi dalam Penelitian Hipnosis
Penelitian hipnosis telah menjadi subjek dari berbagai kontroversi dan perdebatan. Salah satu kontroversi utama menyangkut sifat dari kondisi hipnosis, apakah ia merupakan kondisi kesadaran yang berbeda atau hanya produk dari sugesti dan pengaruh sosial. Kurangnya konsensus tentang masalah ini mencerminkan kompleksitas hipnosis dan tantangan dalam mempelajarinya secara ilmiah.
Kontroversi lain melibatkan penggunaan hipnosis dalam konteks forensik, seperti dalam pemanggilan kembali memori saksi mata atau investigasi peristiwa masa lalu. Potensi untuk menciptakan memori palsu dan pengaruh sugesti menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan dan validitas informasi yang diungkap dengan hipnosis.
Arah Masa Depan dalam Penelitian Hipnosis
Kemajuan dalam Neuroimaging
Kemajuan dalam teknologi pencitraan medis, seperti fMRI dan EEG, menawarkan jalan yang menjanjikan untuk penelitian hipnosis di masa depan. Piranti ini dapat memberikan wawasan terperinci tentang mekanisme otak yang mendasari hipnosis, membantu mengidentifikasi korelasi dan jalur saraf tertentu yang terlibat dalam pengalaman hipnosis.
Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai jenis sugesti hipnotik memengaruhi aktivitas dan konektivitas otak, mengungkap hubungan antara sistem saraf dan fenomena seperti pengurangan rasa sakit, perubahan persepsi, dan pemanggilan ingatan. Memahami mekanisme otak terkait hipnosis juga dapat memberi pengetahuan tentang pengembangan intervensi yang ditargetkan dan aplikasi terapeutik.
Hipnoterapi yang Dipersonalisasi
Pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan individu dalam kemampuan mengalami kondisi hipnosis menunjukkan potensi pendekatan yang bersifat personal. Penyesuaian intervensi hipnotik agar sesuai dengan karakteristik unik individu, seperti tingkat sugestibilitas, ciri-ciri kepribadian, dan kebutuhan spesifik, dapat meningkatkan efektivitas hipnoterapi.
Penelitian di masa depan dapat menyelidiki protokol hipnoterapi yang dipersonalisasi, mengeksplorasi bagaimana berbagai strategi, teknik, sugesti, dan skrip dapat dioptimalkan untuk berbagai populasi dan kondisi. Pendekatan yang dipersonalisasi ini dapat meningkatkan hasil dalam konteks klinis dan memperluas aplikasi hipnosis.
Hipnosis dalam Kesehatan Digital
Integrasi hipnosis dengan teknologi kesehatan digital, seperti aplikasi seluler dan realitas virtual, adalah ranah yang menarik dalam penelitian dan praktik hipnosis. Platform digital dapat memberikan intervensi hipnosis yang mudah diakses dan terukur, sehingga individu dapat memperoleh manfaat dari hipnosis dalam kenyamanan rumah mereka sendiri.
Hipnosis realitas virtual, misalnya, dapat menciptakan pengalaman hipnosis yang imersif dan interaktif, meningkatkan kedalaman dan keefektifan hipnosis. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi kelayakan, penerimaan, dan kemanjuran intervensi hipnosis digital, membuka jalan bagi aplikasi yang inovatif dan mudah digunakan.
Perspektif Lintas Budaya
Penelitian hipnosis sebagian besar dilakukan dalam konteks Barat, tetapi ada minat yang berkembang untuk mengeksplorasi perspektif lintas budaya tentang hipnosis. Budaya yang berbeda bisa jadi memiliki kepercayaan, praktik, dan sikap yang unik terhadap hipnosis, yang dapat mempengaruhi pengalaman hipnosis.
Penelitian di masa depan dapat menyelidiki variasi lintas budaya dalam hipnotisabilitas, penggunaan hipnosis dalam praktik penyembuhan tradisional, dan faktor-faktor budaya yang membentuk penerimaan dan efektivitas hipnosis. Memahami dimensi-dimensi budaya ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih inklusif dan komprehensif tentang hipnosis.
Simpulan
Teori-teori hipnosis memberikan pemahaman yang beragam mengenai fenomena yang terus menggelitik dan menantang para peneliti dan praktisi. Dari perspektif historis yang berakar pada mesmerisme hingga model neurobiologis kontemporer, hipnosis mencakup berbagai penjelasan dan aplikasi.
Teori-teori psikologis, seperti disosiasi, sosial-kognitif, dan model kondisi versus non-kondisi, menawarkan wawasan ke dalam proses kognitif dan sosial yang mendasari hipnosis. Teori neurobiologis menekankan peran aktivitas otak, perubahan neurokimia, dan pola gelombang otak dalam membentuk pengalaman hipnosis.
Aplikasi klinis hipnosis, termasuk manajemen nyeri, psikoterapi, pengendalian kebiasaan, dan prosedur medis, menunjukkan potensi terapeutiknya. Pertimbangan etis dan kontroversi menggarisbawahi pentingnya penggunaan hipnosis yang bertanggung jawab dan berbasis bukti.
Arah masa depan dalam penelitian hipnosis, termasuk kemajuan dalam pencitraan saraf, hipnosis yang dipersonalisasi, aplikasi kesehatan digital, dan perspektif lintas budaya, menjanjikan untuk memperdalam pemahaman kita dan memperluas aplikasi hipnosis.
Kesimpulannya, hipnosis adalah fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang menentang penjelasan sederhana. Interaksi antara faktor psikologis, neurobiologis, dan sosial berkontribusi pada kekayaan pengalaman hipnosis. Penelitian dan eksplorasi hipnosis yang berkelanjutan tidak diragukan lagi akan menghasilkan wawasan dan aplikasi baru, memperkaya pengetahuan kita.


Membangun Kompetensi Induksi Hipnotik
21 Juni 2024Saya membaca laporan proses dan hasil induksi yang dilakukan oleh peserta SECH 2024 dengan sangat antusias. Hanya dalam beberapa hari saja, masing-masing peserta telah melakukan induksi kepada 5, 7, 9, dan 11 klien dengan sangat baik. Mereka semua berhasil menuntun klien masuk kondisi profound somnambulism atau lebih dalam lagi.
Kompetensi melakukan induksi berawal dari proses belajar yang mereka jalani di kelas SECH. Mereka belajar tentang cara kerja, sifat, dan hukum-hukum pikiran secara mendalam, lapisan kesadaran, mulai sadar normal hingga kondisi tidur, indikasi kondisi hipnosis dalam yang digunakan sebagai parameter, berlatih membaca skrip dengan benar di bawah supervisi ketat, mendapat masukan perbaikan dan peningkatan.
Merujuk pada pengalaman pribadi saya saat awal belajar hipnoterapi, saya memahami suasana batin para peserta yang baru pertama kali belajar hipnoterapi. Banyak yang masih kurang percaya dengan kemampuan mereka karena ini adalah hal baru bagi mereka.
Saya melakukan pengecekan di pikiran bawah sadar (PBS) setiap peserta untuk menemukan mental block yang menghambat mereka melakukan induksi: tidak percaya diri, merasa sulit atau tidak mampu, takut gagal. Setelahnya, saya lakukan terapi untuk menetralisir mental block ini dengan cepat.
Di kelas SECH saya juga jelaskan apa yang bisa terjadi atau klien alami saat mereka masuk kondisi hipnosis dalam (profound somnambulism). Semua saya sampaikan agar para peserta ini siap sedia bila jumpa hal-hal tersebut, antara lain:
- Klien bisa mengalami abreaksi spontan, muncul emosi intens, meski tujuan induksi adalah menuntun klien masuk kondisi hipnosis dalam, memberi pengalaman relaksasi tubuh dan pikiran.
Saya jelaskan, berdasar hasil pengukuran gelombang otak yang saya lakukan, menggunakan mesin Mind Mirror, saat individu masuk kondisi hipnosis dalam, gelombang otak dominan adalah theta, yang adalah tempat memori.
Klien bisa bertemu banyak memori, baik positif maupun negatif, yang sebelumnya tidak disadari. Klien bisa bertemu memori traumatik dari masa lalu yang belum terselesaikan, memicu emosi yang terlihat dalam pola gelombang delta dengan amplitudo tinggi.
Saya ajarkan teknik khusus untuk mengatasi situasi ini karena para peserta belum mendapat materi teknik intervensi klinis. Materi ini baru diajarkan di pertemuan minggu kedua.
- Klien bisa mengalami kondisi seluruh tubuhnya kaku, yang disebut catatonia, atau tidak merasakan sebagian atau seluruh tubuhnya, sebagai indikasi kedalaman ekstrem.
- Klien tidak mau keluar dari kondisi hipnosis. Ini sangat jarang terjadi, tapi bisa dan pernah terjadi. Saya jelaskan apa yang sebenarnya klien alami, yang membuat ia tidak mau keluar dari kondisi hipnosis. Saya mengajari peserta cara cepat, mudah, dan aman untuk menuntun klien keluar dari situasi ini.
- Saat dituntun keluar dari kondisi hipnosis, klien bisa mengalami pusing. Saya menjelaskan apa yang terjadi pada klien dan teknik untuk menghilangkan pusing yang klien alami dengan cepat dan mudah.
Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa membangun kompetensi melakukan induksi bukan sekadar memberikan skrip induksi kepada peserta untuk dibacakan kepada klien. Kompetensi melakukan induksi hanya bisa dicapai bila peserta telah mendapatkan pengetahuan yang cukup, pengalaman praktik yang tersupervisi, serta bimbingan berkelanjutan saat mereka praktik mandiri. Hal ini penting untuk memastikan mereka melakukan induksi dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan, yaitu klien masuk kondisi hipnosis dalam.
Para peserta bisa bertanya kepada saya tentang pengalaman induksi mereka dan hal-hal yang belum mereka pahami sepenuhnya melalui grup Telegram. Saya menjawab semua pertanyaan mereka, baik dengan pesan tulisan maupun pesan suara jika diperlukan penjelasan panjang dan mendalam.
Mengapa setiap peserta SECH harus bisa menuntun klien masuk kondisi hipnosis dalam (profound somnambulism)?
Alasan pertama, yang mereka pelajari adalah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis, sehingga kondisi hipnosis adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan hipnoterapi.
Alasan kedua, teknik-teknik intervensi klinis yang diajarkan di kelas SECH mensyaratkan kondisi hipnosis dalam untuk bekerja secara efektif. Dalam kondisi sadar normal, hipnosis dangkal (light trance), dan hipnosis menengah (medium trance), kami tidak bisa melakukan hipnoanalisis secara akurat, mencari, menemukan, dan menyelesaikan trauma dengan efektif dan tuntas.
Berikut ini beberapa pengalaman klien setelah diinduksi dengan skrip 𝐀𝐝𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧:
- Klien bercerita telah didiagnosis ADHD, sudah pernah dua kali melakukan relaksasi dengan terapis berbeda dan tidak berhasil, selalu tidak fokus dan pikirannya loncat ke sana kemari. Saat dinduksi, pada awal pikirannya masih loncat ke sana kemari, tapi selanjutnya bisa mengikuti dan fokus, masuk kondisi hipnosis sangat dalam, sangat relaks, dan nyaman. Saat keluar dari kondisi hipnosis, klien merasa sangat takjub karena baru kali ini ia bisa sangat fokus, relaks, dan sangat nyaman.
- Klien berniat untuk buka mata dan mengatakan ‘Hi’ saat diinduksi, tapi tidak mampu buka mata saking rileksnya.
- Sebelumnya klien sedang dalam kondisi cemas berlebihan. Saat diinduksi badan terasa ngantuk, nyaman, relaks dan setelahnya rasa cemas hilang.
- Klien merasa sangat relaks. Baru kali ini merasakan tubuh dan pikiran bisa serelaks ini, badan segar, enteng.
- Klien merasa tenang, nyaman, badan lebih ringan, pikiran terasa lebih plong tidak ada beban.
- Klien rileks, pikirannya tenang, damai, dan mengantuk, klien diberi sugesti Money Magnet dan ini memunculkan bentuk pikiran ia sedang berdagang dan ada banyak tumpukan uang di depan.
- Saat awal datang klien gelisah, selalu melukai bagian jari jari dengan kukunya. Saat mulai induksi badannya masih gelisah, setelah beberapa saat, klien tenang, merasa nyaman, relaks, dan bahagia sampai merasa tidak mau selesai karena baru pertama kali merasakan hal seperti ini.
- Badan terasa hangat, mengantuk, rileks. Pada saat sugesti Money Magnet, membayangkan uang dan angka di rekening tabungan bertambah, harga crypto naik terus. Setelah keluar dari induksi, merasa uang segera akan datang ke dia, keberuntungan akan datang ke dia segera, percaya diri sekali.
Peserta yang berhasil melakukan induksi pada banyak klien, selain membangun kompetensi induksi, juga mengalami peningkatan rasa percaya diri signifikan. Mereka kini siap masuk ke tahap berikutnya, membangun kompetensi terapeutik yang akan digunakan dalam ruang praktik membantu para klien.
Saya bertanya kepada para peserta tentang perasaan mereka setelah melakukan praktik induksi pada klien. Mereka menjawab bahwa setelah melakukan banyak praktik induksi, mereka menjadi sangat percaya diri, mampu menjiwai cara membaca skrip dengan benar, serta mampu mengatur intonasi dan tempo saat membaca skrip.
Kompetensi tinggi tidak dapat dibangun hanya melalui partisipasi dalam pelatihan atau kehadiran di kelas. Mencapai kompetensi tinggi tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Pencapaian ini memerlukan waktu dan konsistensi. Kompetensi tinggi hanya dapat dibangun melalui proses yang tepat, upaya gigih, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan, disertai dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, serta bimbingan dan pengawasan oleh pengajar yang berpengalaman.
Demikianlah adanya...
Demikianlah kenyataannya...


Tiga Tahap Kritis Menjadi Hipnoterapis Profesional
18 Juni 2024Di saat istirahat makan siang, saya berbincang dengan beberapa peserta di meja makan. Saya tanya mereka, bagaimana mereka tahu tentang pelatihan hipnoterapi Scientific EEG & Clinical Hypnotherapy® (SECH).
Ada yang tahu SECH dari membaca tulisan dan video yang saya tayangkan di media sosial. Ada yang mendapat informasi dari anggota keluarga atau teman yang telah belajar SECH dan berpraktik sebagai hipoterapis aktif. Ada beberapa yang sebelumnya telah menjalani hipnoterapi dengan hipnoterapis AWGI, merasakan manfaat, dan memutuskan untuk belajar agar juga bisa membantu orang lain. Ada yang mendapat referensi dari sejawat ilmuwan psikologi.
Ada yang memang sudah lama berniat belajar hipnoterapi, tidak tahu harus belajar ke mana, dan mencari informasi di internet. Pencarian ini mengantarkan mereka pada beberapa nama pengajar dan lembaga. Setelah mereka mempelajari dengan cermat rekam jejak pengajar atau lembaga yang mengajar hipnoterapi, melakukan pembandingan, akhirnya memutuskan belajar hipnoterapi di AWGI.
Saya berbagi kisah dan pengalaman saya belajar hipnoterapi dengan para peserta. Saya ceritakan betapa sulit saya bisa mendalami hipnoterapi yang efektif dan ilmiah. Saya sampai harus beli sangat banyak buku dan video dari luar negeri. Dan saya harus benar-benar jeli mencari dan menemukan guru-guru hipnoterapi terbaik di dunia. Saya akhirnya memutuskan belajar hipnoterapi langsung ke beberapa pakar hipnoterapi terbaik di Amerika.
Mereka bertanya kepada saya, apa kriteria yang saya gunakan untuk menentukan kualitas guru sebagai tempat belajar saya.
Saya menjelaskan bahwa sebelum menetapkan kriteria untuk guru, saya perlu terlebih dahulu menetapkan tujuan saya dalam mempelajari hipnoterapi. Apakah saya hanya ingin mendapatkan gelar CHt tanpa mempermasalahkan kualitas pelatihan yang diikuti? Apakah saya sekadar ingin mengetahui apa itu hipnoterapi? Apakah saya ingin bisa berpraktik hipnoterapi? Kompetensi seperti apa yang ingin saya capai? Apakah saya ingin bisa menangani kasus ringan, sedang, atau berat?
Saya memilih menjadi hipnoterapis dengan kompetensi terapeutik tinggi, menjadi hipnoterapis terbaik yang saya bisa menjadi. Bagi saya, gelar tidak penting, yang penting adalah kompetensi. Saat saya melakukan terapi, yang dibutuhkan adalah kompetensi, bukan gelar. Oleh karena itu, saya menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pengajar hipnoterapi yang akan saya datangi.
Kriteria ini meliputi, antara lain:
1. 𝐑𝐞𝐤𝐚𝐦 𝐉𝐞𝐣𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐬𝐢: Pengajar harus memiliki rekam jejak sebagai hipnoterapis aktif, cakap, andal, berpengalaman, dengan kredibilitas dan reputasi yang baik.
2. 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐚𝐬𝐢: Pengajar telah menulis minimal satu buku berkualitas yang membahas hipnoterapi.
3. 𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢: Nama pengajar sering disebut atau menjadi rujukan penulis atau praktisi hipnoterapi lainnya.
4. 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢: Pengajar bersedia menunjukkan kompetensinya melalui live therapy di depan murid-muridnya, membuktikan teori, strategi, dan teknik terapi yang diajarkan.
5. 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬: Alumni pelatihannya terbukti memiliki kompetensi terapeutik tinggi dan aktif berpraktik.
6. 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐭𝐚𝐩 𝐌𝐮𝐤𝐚: Pelatihannya harus diselenggarakan secara tatap muka.
7. 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐈𝐥𝐦𝐢𝐚𝐡: Menulis artikel jurnal tentang hipnoterapi (opsional).
Dengan menggunakan kriteria ini, saya bertemu dengan guru-guru hipnoterapi terbaik dunia seperti Gil Boyne, Randal Churchill, Gerald Kein, John Butler, Tom Silver, dan Anna Wise. Semua guru ini melakukan live therapy di kelas, menangani klien dengan masalah riil, bukan sekadar simulasi. Ini memungkinkan kami sebagai murid melihat, belajar, dan memahami proses hipnoterapi yang benar dan efektif dari awal hingga akhir.
Pengalaman belajar dengan guru-guru saya ini menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Sejak pertama saya menyelenggarakan pelatihan hipnoterapi profesional di tahun 2008, saya melakukan live therapy sebagai bagian dari proses pendidikan untuk menghasilkan hipnoterapis profesional berkompetensi terapeutik tinggi.
Untuk memastikan setiap peserta didik SECH mampu menumbuhkembangkan kompetensi terapeutik tertinggi yang bisa mereka capai, saya memutuskan menaikkan standar proses pendidikan hipnoterapis lebih tinggi lagi, dengan memberikan bimbingan dan supervisi pada setiap praktik yang dilakukan para peserta didik SECH.
Ini bukan hal mudah karena sangat menyita waktu, menguras energi dan pikiran saya. Saya membaca setiap laporan kasus terapi yang dilakukan para peserta SECH, menilai, dan memberi saran, masukan untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi mereka.
Keputusan ini didasarkan pada pengalaman pribadi saya. Saya tahu betapa sulitnya mencapai kompetensi tinggi tanpa bimbingan dan supervisi ketat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan oleh pengajar berpengalaman.
Berdasar pengalaman saya, ada tiga tahap kritis yang harus dilalui setiap peserta didik untuk menjadi hipnoterapis kompeten:
1. 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐨𝐫𝐢: Peserta harus memahami landasan teori yang kuat, pengetahuan yang mendalam tentang cara kerja pikiran, pendekatan, metode, strategi, dan teknik-teknik terapi yang telah teruji, terbukti aman, dan efektif. Tahap ini sangat penting karena menjadi landasan untuk tahap-tahap berikutnya.
2. 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 𝐇𝐢𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬: Peserta harus mampu melakukan induksi dan berhasil menuntun klien masuk ke kedalaman kondisi hipnosis yang tepat untuk melakukan terapi. Keberhasilan induksi membangun rasa percaya diri yang sangat penting dalam praktik hipnoterapi. Di kelas SECH, selain menjelaskan landasan teori dari skrip induksi yang digunakan, saya juga menunjukkan cara penggunaan skrip yang benar dengan melakukan induksi pada peserta.
3. 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢: Peserta harus mampu melakukan praktik mandiri yang efektif dan sukses membantu klien, karena keberhasilan pada tahap awal ini sangat penting untuk menguatkan kepercayaan diri mereka. Ini hanya bisa dicapai jika peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar dan mendalam tentang hipnoterapi, mampu melakukan induksi dengan berhasil, dan telah melihat secara langsung bagaimana terapi dilakukan. Saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari empat video rekaman live therapy yang saya lakukan di angkatan SECH sebelumnya dan melakukan empat live therapy di depan kelas.
Peserta juga diberi basis data dan pengalaman terapi sejak minggu pertama hingga hari terakhir pendidikan. Saya menceritakan berbagai kasus yang pernah saya dan hipnoterapis AWGI tangani, strategi dan teknik yang digunakan, dan hasil terapi yang dicapai.
Dengan pendekatan ini peserta dapat menjadi hipnoterapis profesional dengan kompetensi terapeutik tinggi, mampu membantu klien secara efektif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.


Otak Tidak Bisa Menerima Kata Negatif: Kata Siapa?
9 Juni 2024

Live Therapy Sebagai Landasan Kompetensi Terapeutik
5 Juni 2024Salah satu sejawat hipnoterapis AWGI, alumnus SECH tahun 2023, kirim pesan melaporkan kasus yang ia tangani. Kasus pertama, fobia terbang dengan pesawat. Kasus ini di permukaan tampak sederhana, namun di baliknya terdapat akar masalah serius. Kasus kedua, klien dengan kecenderungan melakukan tindakan bunuh diri. Ia mampu menangani keduanya dengan sangat baik dan tuntas, masing-masing dalam satu sesi terapi. Hasil tindak lanjut pada kedua klien ini, sebulan kemudian, didapatkan hasil bahwa keduanya sangat baik dan stabil kondisinya.
Sejawat ini secara khusus menyampaikan terima kasih karena saat mengikuti pendidikan hipnoterapis di AWGI, ia berkesempatan tidak hanya menonton dan mempelajari video rekaman live therapy, juga terutama ia menyaksikan langsung live therapy yang saya lakukan di depan kelas.
Menurutnya, dengan menyaksikan live therapy ia belajar cara cepat membangun relasi terapeutik yang kuat, membangun rasa percaya dan aman dalam diri klien sehingga klien bersedia terbuka dan menceritakan masalahnya.
Ia menjadi lebih cermat dan teliti saat mendengar cerita klien dan mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah klien sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Ia mendapat "feel" bagaimana sikap, perhatian, keyakinan dan hati terapis saat membantu klien di ruang praktik.
Dan yang juga sangat penting, ia menyaksikan langsung, belajar, dan mengerti cara efektif dan efisien dalam menggunakan strategi dan teknik terapi seturut dinamika yang terjadi di ruang praktik. Menurutnya, ia mengerti bagaimana menjadi peka, tanggap, dan lentur dalam membantu klien. Pembelajaran ini berdampak signifikan dan memampukan dirinya bekerja optimal membantu klien.
Saya menyadari bahwa proses hipnoterapi sangat kompleks. Sejak pertama kali saya mengajar hipnoterapi di tahun 2008, hingga saat ini, saya menetapkan live therapy di depan kelas sebagai salah satu syarat mutlak untuk membangun kompetensi terapeutik setiap peserta didik.
Berdasar pengalaman saya belajar dan membangun kecakapan terapi, terapis pemula tidak akan bisa membangun kompetensi terapeutik tinggi hanya dengan mendapat pelajaran di kelas, baca workbook, nonton video, dan kemudian langsung praktik mandiri. Bila ini yang terapis pemula lakukan, sama seperti saya dulu, yang terjadi adalah kebingungan, tak tahu arah, dan akhirnya mengalami kegagalan berulang.
Hipnoterapis pemula sangat butuh melihat langsung proses terapi yang benar agar mereka memilik basis data yang kuat sebagai acuan dan tolok ukur (benchmark). Mereka juga butuh mendapat bimbingan berkelanjutan hingga akhirnya mencapai standar kompentensi yang ditetapkan.
Di kelas SECH saya menunjukkan langsung aplikasi ilmu yang diajarkan di kelas ke dalam praktik nyata. Masalah yang saya tangani tidak boleh masalah ringan atau sederhana seperti fobia. Masalahnya harus cukup kompleks sehingga teknik yang diajarkan di kelas dapat dipraktikkan dan ditunjukkan dengan segala dinamikanya.
Saat peserta didik melihat langsung teknik yang mereka pelajari berhasil membantu klien mengatasi masalah, pengalaman dan bukti ini menumbuhkan rasa percaya diri kuat bahwa mereka pun pasti bisa.
Saya melakukan total empat sesi live therapy di depan kelas, dengan klien yang berasal dari luar peserta. Jika klien adalah peserta workshop, proses terapinya tidak dapat menunjukkan dinamika yang terjadi di ruang praktik, karena peserta mengenal saya sebagai pengajar dan figur otoritas. Sebaliknya, jika klien berasal dari luar dan tidak mengenal saya, proses terapi berjalan persis seperti yang terjadi di ruang praktik saya.
Di kelas SECH saya hanya mengajarkan teknik yang saya gunakan di ruang praktik. Teknik-teknik ini telah teruji aman dan efektif mengatasi masalah klien dengan cepat dan tuntas. Saya tidak mengajarkan teknik yang belum pernah saya gunakan, walau di berbagai literatur diklaim efektif. Teknik yang saya ajarkan adalah intisari dari hasil belajar, praktik, dan temuan kami sejak tahun 2005 hingga kini.
Di awal karir saya sebagai hipnoterapis, saya punya banyak sekali teknik untuk kasus berbeda. Misal, untuk menangani klien yang mengalami fobia, saya gunakan teknik A. Untuk masalah kecemasan, teknik B. Masalah adiksi, teknik C. Untuk insomnia, teknik D. Kebiasaan menunda, teknik E, dan seterusnya.
Karena ada banyak teknik yang harus saya ingat, saya sering mengalami kebingungan. Setiap kali menangani klien, saya tidak dapat fokus mendengarkan dan memahami masalah mereka, karena pikiran saya justru sibuk memikirkan teknik mana yang akan saya gunakan.
Kondisi ini menjadi semakin rumit bila ternyata masalah klien bersifat multilayer atau berlapis. Misal klien mengalami adiksi rokok. Dari hasil wawancara diketahui klien merokok karena stres. Ia stres karena sedang ada masalah di pekerjaan. Bila seperti ini kondisinya, teknik apa yang akan digunakan?
Akhirnya, saya memutuskan untuk menyederhanakan proses terapi. Melalui proses yang tidak mudah, selama tiga tahun saya mengamati dan mempelajari setiap masalah klien untuk menemukan pola. Saya juga membaca buku dan artikel jurnal. Dengan memahami pola-pola tersebut, penanganan setiap masalah dapat menggunakan protokol yang sama, meskipun dengan dinamika yang berbeda.
Pola yang saya temukan, untuk setiap masalah (simtom) pasti ada sebab (akar masalah). Bila ada asap, pasti ada api. Cari, temukan, dan padamkan apinya, maka asap dengan sendirinya pasti hilang.
Dengan logika yang sama, jika saya bisa membantu klien mencari, menemukan, dan menyelesaikan akar masalahnya, maka masalah klien akan berhasil diatasi. Setelah hati-hati dan cermat menelaah serta mengujicobakan berbagai teknik, merujuk pada buku teks, artikel jurnal, serta pengalaman dan temuan di ruang praktik, saya akhirnya memutuskan untuk fokus hanya pada dua teknik utama. Semua teknik lainnya, yang sebelumnya cukup merepotkan, saya tinggalkan.
Dua teknik ini, dengan varian strateginya, telah diterapkan dalam lebih dari 130.000 sesi konseling dan terapi selama hampir 20 tahun dengan hasil yang sangat baik. Teknik-teknik ini terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan temuan dan pembelajaran kami, para hipnoterapis AWGI.
Mengingat proses pendidikan yang sangat intensif, saya mewajibkan setiap peserta didik untuk hadir dan mengikuti program pendidikan hipnoterapis SECH secara lengkap dan utuh selama 110 jam tatap muka atau 10 hari. Jika ada peserta yang, karena alasan tertentu, tidak dapat hadir meskipun hanya setengah hari, sesuai ketentuan, mereka harus mengundurkan diri.
Seluruh proses pendidikan SECH dilaksanakan secara tatap muka dan tidak dapat dilakukan secara daring (online), karena proses belajar tidak hanya sekadar melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh pengajar seperti yang terjadi dalam pembelajaran daring.
Proses belajar yang baik dan benar melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada perbedaan yang signifikan dalam hal pengalaman dan dampak antara pembelajaran daring dan tatap muka. Hal ini juga berlaku untuk menyaksikan live therapy, baik secara daring maupun langsung di kelas.
Hipnoterapis pemula, yang dibekali dengan rasa percaya diri yang tinggi, mampu melaksanakan praktik sesuai protokol dengan hasil yang sangat baik. Ini tidak hanya membangun kompetensi terapeutik mereka tetapi juga semakin meningkatkan dan memperkuat rasa percaya diri mereka.
Sebaliknya, hipnoterapis yang kurang percaya diri atau meragukan kemampuan dan kompetensinya karena tidak menerima pendidikan dan bimbingan yang tepat, tidak akan mampu melaksanakan hipnoterapi dengan benar dan efektif. Semakin mereka tidak percaya diri, semakin tidak efektif terapi yang mereka lakukan.
Hipnoterapis tidak kompeten bisa saja mendapat klien lewat promosi yang dilakukan di media sosial. Namun, bila ia berulang kali gagal membantu klien-kliennya, rasa percaya dirinya pasti akan terdampak hingga akhirnya ia memutuskan berhenti praktik. Tentunya ini sangat disayangkan, mengingat investasi waktu, tenaga, dan biaya yang telah ia keluarkan, dan terutama jumlah hipnoterapis profesional masih sangat sedikit di Indonesia.


Terapi Singkat
30 Mei 2024